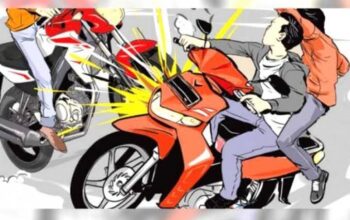Irvin Toefler memiliki sudut pandangnya sendiri mengenai pembagian evolusi sejarah peradaban dunia. Toefler membaginya ke dalam tiga gelombang: 1) Era Pertanian, 2) Era Industri, 3) era Informasi. Pada era pertanian, faktor yang menonjol agar tetap survive dalam menjalani kehidupan adalah muscle (otot), era ini ditandai dengan dominasi penggunaan otot dalam meningkatkan produktivitas.
Irvin Toefler memiliki sudut pandangnya sendiri mengenai pembagian evolusi sejarah peradaban dunia. Toefler membaginya ke dalam tiga gelombang: 1) Era Pertanian, 2) Era Industri, 3) era Informasi. Pada era pertanian, faktor yang menonjol agar tetap survive dalam menjalani kehidupan adalah muscle (otot), era ini ditandai dengan dominasi penggunaan otot dalam meningkatkan produktivitas.
Selanjutnya era indutri ditandai dengan masuknya mesin-mesin teknologi untuk mengantikan pekerjaan otot. Penggunaan (machine) dinilai oleh masyarakat saat itu lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas, serta efisien dari segi biaya. Selanjutnya, terakhir adalah era informasi. Dalam era yang terakhir ini, faktor yan menonjol adalah pemikiran dan pengetahuan (Mind).
Era informasi ini adalah era yang sedang kita jalani saat ini. Pada era ini, informasi memiliki pengaruh yang amat sangat besar dalam menentukan kemajuan inividu dan organisasi. Bangsa yang mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi era yang ketiga ini, maka dapat dipastikan mampu survive untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Sebaliknya, seseorang yang tertinggal dalam perkembangan informasi kekinian, resikonya tak bisa di tawar lagi: ia harus rela tertinggal dan diam di tempat.
Era informasi sebagai fenomena hubungan kausalitas dari perkembangan teknologi informasi telah mengaburkan batas yang bukan hanya batas yang bersifat fisik, namun juga non fisik; ruang dan waktu. Kaburnya batas-batas itu telah memunculkan sebuah istilah yang oleh penulis di sebut dengan Global Village.Selalu ada dua sisi dari berbagai fenomena, begitu pula dengan hal ini. Bagi sebagian masyarakat, keterbukaan informasi menjadikan semuanya menjadi mudah. Tidak terhalang batas dan waktu. Telleconference misalnya, teknologi ini mampu mempertemukan dua orang tanpa memerlukan kehadiran fisik. Tentu teknologi semacam ini sangat membantu.
Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat fenomena keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi ini sebagai bumerang bagi generasi mendatang. Sikap-sikap yang selama ini dianggap bertolak belakang dengan budaya tanah air bisa begitu saja muncul dipicu oleh kemajuan teknologi yang semakin menggila ini. Bahkan tidak perlu menunggu lama. Sekarang pun sudah tampak. Prinsip Gotong royong, kekeluargaan, tenggang rasa, serta sikap adiluhung lain yang diajarkan ketika SD, serta diyakini sebagai ciri khas masyarakat Indonesia, kini mulai pudar dan tergantikan oleh sikap yang lebih apatis dan individualis.
Over dosisnya teknologi informasi akan atau bahkan telah mengabu-abukan identitas sebuah bangsa bahkan mengabu-abukan kebenaran dari informasi (Pengetahuan) itu sendiri. Ironisnya, jika tidak disikapi secara bijak dan up to date, maka akan semakin banyak bermunculan generasi-generasi yang memiliki pandangan kuno (tertinggal) dan abu-abu terhadap sebuah kebenaran. Hal semacam ini bisa terjadi karena pada dasarnya sebuah informasi (pengetahuan) akan mudah sekali mengalami keusangan oleh sebab itu perlu diperbaharui secara menerus melalui proses belajar.
Proses belajar tidak hanya bertujuan sebagai jalan untuk menciptakan generasi yang mampu mencerna dan menganalisis kebenaran dari sebuah informasi, akan tetapi merupakan jalan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk menghadapi perubahan besar agar mampu survivedi era yang ketiga ini. Jika diidentifikasi, maka ada dua permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa kita dalam era ini:
1) Mempertahankan identitas bangsa yang mulai memudar sebagai akibat dari keterbukaan informasi teknologi.
2) menyiapkan generasi penerus agar mampu membawa bangsa ini survive di era informasi yang semakin pesat.
Kedua masalah ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan mampu diselesaikan dengan sekali jalan, yaitu melalui paradigma pendidikan. Kita semua sadar dan tahu persis bahwa salah satu tujuan fundamental dari pendidikan bukan hanya menyiapkan generasi masa datang yang mampu survive dengan berbagai keadaan, akan tetapi juga untuk melestarikan karakter sebuah bangsa.
Kita semua tahu bahwa paradigma pendidikan kita yang sekarang adalah peninggalan dari paradigma pendidikan yang lama. Di sisi lain, agar bangsa kita mampu survive serta tidak tergerus oleh perubahan jaman global yang absolut, maka perubahan paradigma pendidikan ini mutlak dillakukan. Paradigma pendidikan ideal untuk menciptakan generasi yang mampu survive dalammainstream di atas, adalah pendidikan yang menjunjung tinggi kreativitas dan melatih peserta didik agar lebih memiliki sifat kritis. Mengalir derasnya informasi yang tidak dapat dibendung, memungkinkan seseorang untuk menciptakan hal baru, namun juga menyebabkan seseorang tenggelam dalam timbunan informasi yang membingungkan karena sulitnya membedakan informasi yang valid dan tidak valid, maka dari itu, sikap kreatif dan kritis mutlak dimiliki untuk mengantisipasi hal demikian. Begitupun untuk lembaga perguruan tinggi, perguruan tinggi perlu melakukan hubungan partisipatif dengan masyarakat dan lembaga penelitian, pasalnya selama ini hubungan diantara lembaga-lembaga tersebut terkesan bersifat formal dan seremonial, bahkan cenderung menjaga jarak dengan keangkuhannya masing-masing.
Terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, dan untuk memenuhi tuntutan abad 21 diperlukan perubahan paradigma serta reorientasi dalam pembelajaran yaitu dari; 1) Merubah paradigma pembelajaran dari paradigma memindahkan secara utuh pikiran guru ke pikiran siswa, menuju pembelajaran yang lebih memberdayakan seluruh kemampuan aspek siswa. 2) Merubah paradigma Teacher centered learning, menjadi Student centered learning. 3) Merubah paradigma menghafal menjadi paradigma menemukan dan membangun. 4) Merubah paradigma pembelajaran individual klasikal menjadi pembelajaran kooperatif yang dapat melatih keterampilan sosial.
Perubahan paradigma itu perlu dipahami tidak hanya oleh pendidik, namun juga oleh para calon pendidik yang sekarang masih duduk dibangku kuliah. Pasalnya, jika pendidik dan calon pendidik telat dalam merubah paradigma pendidikan, maka taruhannya adalah generasi yang dilahirkan. Mereka akan tertinggal oleh perubahan jaman dan terlindas oleh kesemrawutan yang terjadi sekarang ini.
Di sisi lain, permasalahan ini tidak dapat disalahkan pada satu pihak saja, pasalnya agar bangsa kita bisa survivedalam era informasi, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, serta masyarakat, seluruhnya berperan aktif! Khusus untuk saya pribadi serta rekan-rekan sesama calon pendidik, semoga kita mampu untuk intropeksi diri agar secepatnya dapat berbenah untuk kebaikan kita semua.
Penulis: Dede Kurnia, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi